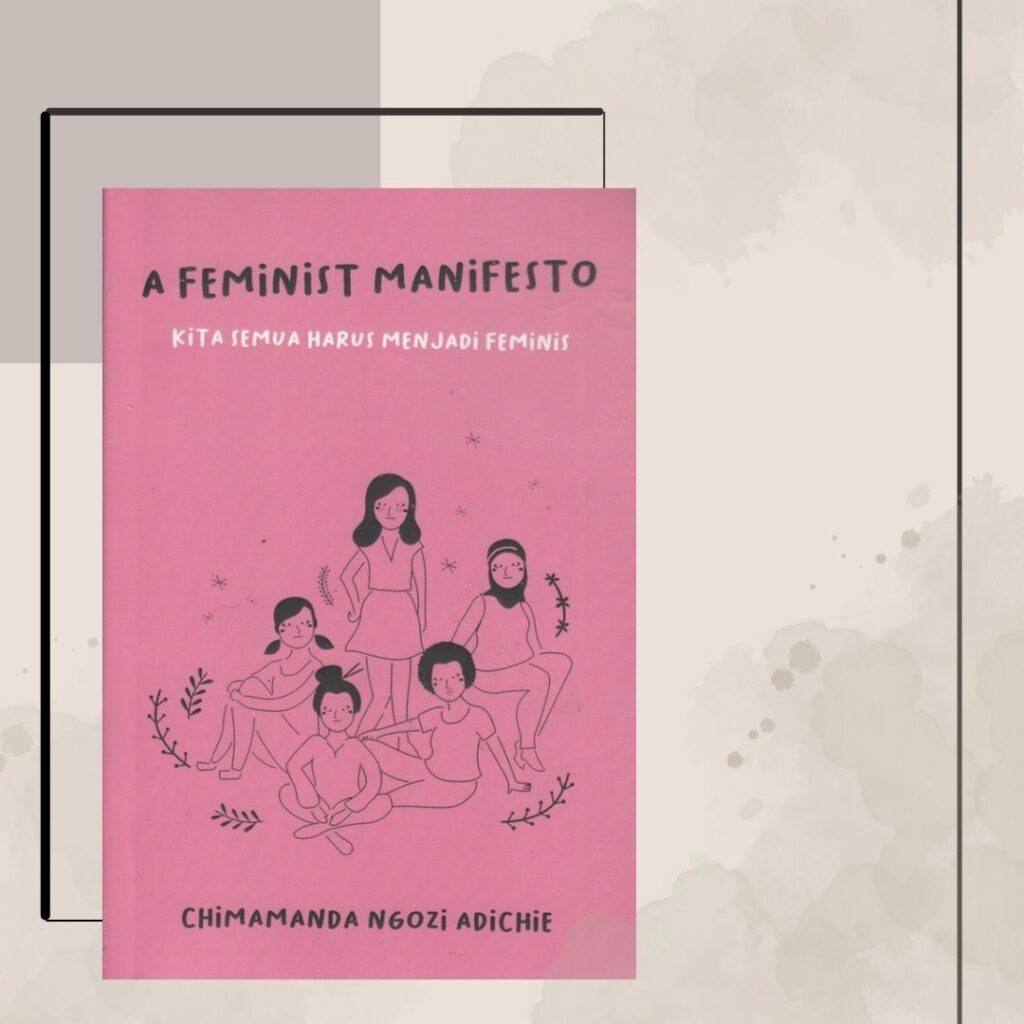“Kok beli baju warna pink, sih? Dia kan lak-laki bukan perempuan. Seharusnya beli bajunya warna biru atau cokelat.”
“Masa jatuh dari sepeda aja nangis. Anak laki-laki itu gak boleh nangis, harus kuat. Malu sama anak perempuan lainnya.”
“Jadi anak perempuan itu harus kalem dan sabar. Kalau ada yang ganggu kamu di sekolah, biarin aja, gak usah dilawan. Anak perempuan gak boleh kasar.”
Sering kali saya mendengar kalimat-kalimat di atas diucapkan oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Sehingga anak yang terus-menerus diberikan label tersebut, tanpa disadari menjadi sebuah doktrin yang tidak jelas alasannya. Ini tertanam dan akan diingat oleh anak hingga ia dewasa. Tentu, menjadi bibit kesenjangan identitas dan gender serta nilai-nilai sosial absurd yang akan diteruskan ke generasi selanjutnya.
Saat ini, sangat sulit kita menemukan orangtua yang memberikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya anak mengetahui konsep kesetaraan gender, penerimaan diri dan keterbukaan terhadap perbedaan. Anak sejak kecil selalu dicecoki dengan budaya usang dan nilai standarisasi universal tanpa memberikan ruang bagi anak untuk bertanya ‘kenapa’. Padahal, memberikan pemahaman-pemahaman inklusi tersebut, orangtua sudah memenuhi hak-hak anak yang harus dipenuhi. Hak untuk memilih jalannya sendiri, hak untuk melindungi diri, hak untuk mendapat pengakuan dan hak untuk merasa aman.
Keresahan saya ini akhirnya dijawab dalam buku “A Feminist Manifesto: Kita Semua Harus Menjadi Feminis,” karya Chimamanda Ngozi Adichie. Buku serial yang dapat memberikan konsep kesetaraan gender dan inklusi kepada anak hanya dalam waktu 60 menit saja. Adichie memberikan analisis kritis namun dengan kalimat yang mudah dimengerti, tentang mengapa dan bagaimana orang tua mengajarkan nilai kesetaraan gender kepada anak sejak mereka usia dini. Bukan tanpa sebab, Adichie pun berangkat dari keresahan masa kecilnya, di mana seorang anak laki-laki terpilih sebagai ketua kelas, padahal jabatan itu dijanjikan gurunya sebagai imbalan atas kompetisi yang dimenangkannya.
Buku “A Feminist Manifesto: Kita Semua Harus Menjadi Feminis” ini merupakan penggabungan dua buku kumpulan esai Adichie; “We Should All Be Feminists” yang terbit pada tahun 2014 dan “Dear Ijeawele, or a Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions” yang terbit pada tahun 2017. Sudah dialihbahasakan ke bahasa Indonesia dan diterbitkan sebuah penerbit di Yogyakarta, Odyssee Publishing. Buku berisi 79 halaman, cetak pertama sekali pada Agustus 2019. Desainnya menarik dengan sampul berwarna merah muda dan ilustrasi lima orang perempuan yang menggambarkan keberagaman identitas perempuan.
Dalam bukunya, Adichie seakan ingin menyampaikan kepada semua orang tua bahwa anak adalah generasi yang akan meneruskan keberlangsungan tatanan sosial kehidupan selanjutnya. Ditangan mereka, sebuah keputusan besar mau dibawa ke mana kehidupan sosial manusia nantinya. Untuk itu, Adichie merasa mengajarkan nilai feminisme kepada anak adalah solusi paling tepat untuk memberikan anak bekal pengetahuan agar terwujudnya kehidupan yang berkeadilan.
Salah satu penggalan kalimat yang membuat Adichie resah akan kondisi pengajaran orang tua pada zaman modern ini adalah: “Kami bilang pada anak perempuan kami, ‘kamu boleh punya ambisi, tapi jangan terlalu berlebihan. Kamu boleh untuk sukses tetapi jangan terlalu sukses, jika tidak, kamu akan mengancam keberadaan laki-laki. Dan kalau suatu saat kamu menikah dan kamu bertugas mencari nafkah, anggaplah kamu bukan pencari nafkah.”
Betapa menyedihkan, orang tua melakukan tindakan yang sangat merugikan otonomi anak perempuan, karena masyarakat telah mengondisikan kita untuk membesarkan anak perempuan demi memenuhi ego anak laki-laki. Anak perempuan diajari sejak lahir bahwa tidak ada yang lebih buruk daripada pelemahan anak laki-laki. Pada gilirannya, anak perempuan diajari untuk membungkam diri mereka sendiri, untuk selalu menahan diri terhadap apa yang sebenarnya mereka pikirkan.
Dibuku inilah Adichie bekerja. Alih-alih feminisme adalah kata yang sarat muatan dan mengundang banyak kontroversi dan kritik baik dari laki-laki maupun perempuan, pada intinya – menjadi feminisme berarti membangun dan mencapai kesetaraan politik, ekonomi, pribadi, dan sosial bagi kedua jenis kelamin. Dari buku ini, Adichie memberikan beberapa tips sederhana bagaimana memberikan ajaran yang dapat menumbuhkan konsep kesetaraan gender dan inklusi kepada anak:
Ajari untuk menolak ‘disukai.” Pekerjaannya bukan untuk membuat dirinya disukai, tetapi menjadikan dirinya secara penuh, diri yang jujur dan sadar akan kemanusiaan yang setara satu sama lain. Ajari untuk berani. Berani mengungkapkan pikirannya, untuk mengatakan apa yang sebenarnya ia pikirkan dan berbicara dengan jujur. Ajari untuk mengatakan bahwa kebaikan itu penting. Memuji anak ketika dirinya melakukan kebaikan kepada orang lain. Namun, ajari juga bahwa kebaikannya tidak boleh diremehkan. Mengatakan bahwa dia juga pantas mendapatkan kebaikan orang lain. Mengajari untuk membela apa yang menjadi miliknya. Mengatakan kepada anak bahwa jika ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, maka dia harus berbicara, harus mengatakannya atau bahkan berteriak.
Menunjukkan pada anak bahwa dia tidak perlu disukai oleh semua orang. Mengatakan padanya bahwa jika seseorang tidak menyukainya, maka ada orang lain yang akan menyukainya. Mengajari bahwa dirinya bukan objek untuk disukai dan tidak disukai, tetapi juga subjek yang bisa menyukai dan tidak menyukai. Mengajari anak untuk mempertanyakan penggunaan biologi selektif budaya yang dijadikan ‘alasan’ untuk norma-norma sosial yang kadang absurd. Ajari bahwa biologi adalah subjek yang menarik dan memesona, tetapi dia tidak boleh menerimanya sebagai pembenaran atas kekerasan apa pun, atau menerimanya sebagai pembenaran atas norma sosial. Karena norma sosial diciptakan oleh manusia, dan tidak ada norma sosial yang tidak dapat diubah.
Mengajari tentang kasih. Bahwa mencintai bukan hanya soal memberi tetapi juga menerima. Selama ini banyak orangtua mengajari anaknya, khususnya anak perempuannya untuk mencintai adalah kemampuan mereka mengorbankan diri sendiri. Tetapi ajari anak untuk memberikan dirinya secara emosional juga mengharapkan hal yang sama untuk dirinya.
Mengajarinya soal perbedaan. Membuat perbedaan menjadi hal biasa baginya. Membuat perbedaan menjadi suatu yang normal. Mengajari untuk tidak memberikan nilai pada perbedaan. Karena perbedaan adalah realitas dunia kita. Dengan mengajarinya perbedaan, berarti melengkapi dirinya untuk bertahan hidup di dunia yang beragam ini. Mengajari dia untuk tidak menguniversalkan standar atau pengalamannya sendiri. Mengajari dia bahwa standarnya hanya untuk dirinya sendiri, dan bukan untuk orang lain. Pedagoginya, bahwa perbedaan itu normal.
Mengatakan padanya bahwa beberapa nantinya, setelah mereka dewasa, ada orang yang menikah dan beberapa yang tidak. Seorang anak kecil bisa memiliki dua ayah dan dua ibu, dan itu normal. Memberitahu dia bahwa beberapa orang pergi ke masjid, yang lain ke gereja, yang lain pergi beribadah ke tempat-tempat yang berbeda dan yang lain tidak beribadah sama sekali. Dengan begitu, anak akan menjadi manusia yang penuh dengan pendapat, dan pendapatnya didasari oleh wawasan yang luas dan manusiawi.
Hal terpenting yang dapat diambil dari buku ini adalah bahwa kesenjangan antar jenis kelamin merupakan konstruksi sosial dan budaya, yang telah tertanam dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui cara kita membesarkan anak. Masalah dengan gender adalah bahwa gender menentukan bagaimana kita seharusnya bersikap, bukan mengakui bagaimana diri kita sebenarnya. Bayangkan betapa bahagianya anak-anak, betapa lebih bebasnya diri mereka yang sebenarnya, jika orang tua tidak memiliki beban terhadap ekspektasi gender.
Buku ini penting bukan karena saya ingin para orangtua semuanya menjadi feminis, namun karena pencapaian kesetaraan gender di bidang sosial, politik, dan ekonomi sangat penting bagi kemajuan budaya dan evolusi global. Buku ini memberikan perspektif yang kuat, penting, dan mungkin agak tidak nyaman mengenai ketidakadilan dan ketidaksetaraan antar jenis kelamin. Namun saya yakin inilah saatnya bagi kita untuk membangun kemungkinan adanya hubungan dan pemahaman untuk menjembatani kesenjangan perbedaan pendapat. Sudah waktunya bagi kita, terkhusus orang tua, untuk berbuat lebih baik lagi.