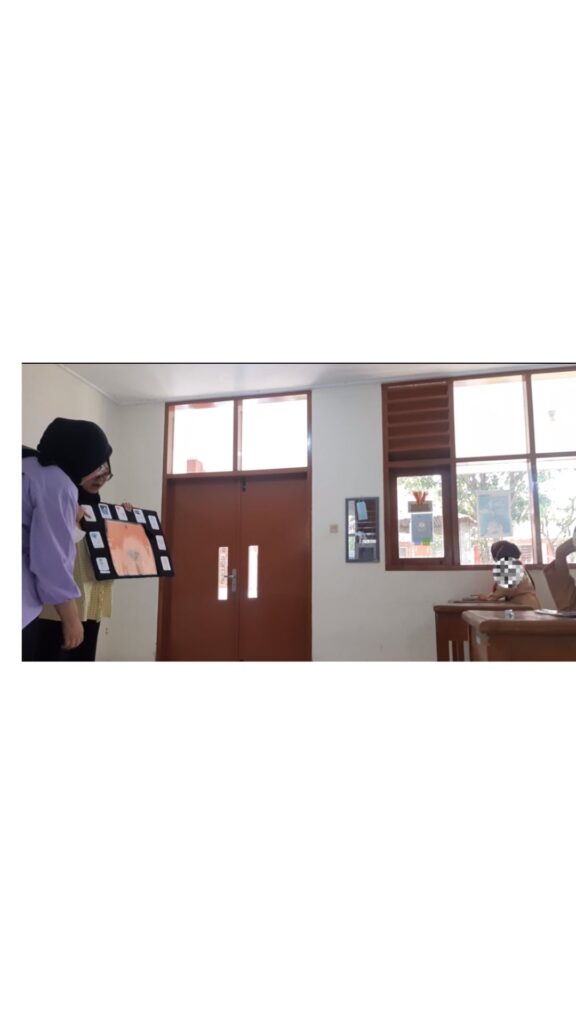Nida Nurhamidah, Sofi Septiani dan Chintia Khoirunnisa, mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), jurusan Pendidikan Khusus, melakukan penelitian dan edukasi terkait alat reproduksi perempuan dan fungsinya kepada anak penyandang disabilitas di Bandung.
Nida menjelaskan perkembangan zaman terutama dalam arus digitalisasi tidak menjadi jaminan bahwa pengetahuan tentang isu hak kesehatan reproduksi dan seksualitas (HKRS) dapat diakses dengan baik. Terbukti, masih banyaknya masyarakat yang menganggap tabu isu ini. Sehingga menjadi dampak bagi anak-anak khususnya mereka yang menyandang disabilitas.
“Kayak sekolah di daerah Bandung tempatku melakukan penelitian. Ketika aku tanya atau aku tunjukkan gambar alat reproduksi, mereka ketawa dan malu-malu untuk menjawab,” jelas Nida.
Anggapan orang tua atau keluarga bahwa isu HKRS adalah isu yang tidak seharusnya diketahui oleh usia anak-anak menjadi faktor utama, kata Nida. Hal ini juga yang pernah dirasakan oleh Nida sewaktu masa anak-anak.
“Dulu waktu aku mengalami pubertas, aku malu dan menutupi ini dari orangtuaku. Karena kalau aku terbuka, keluarga akan memojokkan dan menganggap bahwa aku dewasa sebelum waktunya,” kenang Nida.
Nida menambahkan proses pubertas dan perubahan organ reproduksi bukan lah hal yang salah. Jika dilihat secara kodrati dan secara usia perkembangan, semua orang pasti melewati hal tersebut. Sayangnya gambaran nilai-nilai tabu ini lah yang kerap kali dicekcoki dari orang tua dan keluarga kepada anak-anak sejak usia dini.
Isu HKRS menjadi penting karena ini akan meningkatkan kepekaan dan pengenalan anak terhadap tubuh mereka sendiri. Menjadi pencegahan dini bagi anak agar tidak mengalami penyakit reproduksi dan kekerasan seksual.
“Apalagi untuk anak disabilitas. Mereka sangat rentan sekali mengalami kekerasan seksual. Karena tidak mendapatkan edukasi dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas yang setara dengan anak-anak lainnya,” tegasnya.
Pun, pendidikan tentang HKRS masih banyak yang tidak transparan. Sehingga, perlu penyesuaian yang lebih tepat agar edukasi ini dapat disampaikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dengan tepat sasaran.
Tidak hanya itu, dependensi orang tua yang tinggi pun turut menjadi tantangan terbesar bagi Nida dan kawan-kawan dalam memulai edukasi. Adanya anggapan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus adalah individu yang tidak dapat hidup mandiri. Pun, hanya orang tua lah yang paling tahu tentang kebutuhan anaknya.
“Ini menjadi sulit karena dari awal orang tua maupun keluarganya gak terbuka. Kami dianggap mengajari hal yang gak benar kepada anak mereka.”
Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan, Nida menuturkan bahwa dirinya dan teman-temannya menemukan beberapa fakta yang menarik. Pertama, terkait pengetahuan tentang konsep dasar dari kesehatan reproduksi dan seksualitas yang tidak pernah didapat oleh anak-anak disabilitas. “Mereka masih belum paham bahwa konsep dasar seperti sesuatu yang kotor itu harus dibersihkan dan yang basah harus dikeringkan.”
Belum lagi, kurangnya tenaga pendidik perempuan yang menyampaikan edukasi terkait isu HKRS ini. Kebanyakan, kata Nida, edukasi isu HKRS disampaikan oleh tenaga pendidik laki-laki sehingga adanya rasa malu bagi anak perempuan untuk terbuka. Terakhir, orang tua yang sibuk sehingga lupa untuk memperhatikan proses perkembangan seksualitas anaknya.
“Ini akhirnya menambah pemahaman kami. Di mana selain melakukan intervensi kepada anak, kami harus terlebih dahulu melakukan intervensi kepada orang tua mereka,” jelas Nida.
Dari hasil pengamatan itulah, Nida dan kawan-kawan akhirnya berinisiatif menciptakan edukasi yang semi konkret dan interaktif. Mereka pun membuat papan edukasi yang dinamai dengan Papan Poppy. Nama ini diambil dari bunga Poppy. Bentuknya seperti vagina dan jika tidak dirawat dengan baik akan mengeluarkan bau yang tidak sedap.
Papan Poppy ini berisikan pengetahuan dasar tentang bagaimana anak disabilitas dapat mengenal organ reproduksi mereka beserta dengan fungsinya. Juga, bagaimana merawat alat reproduksi mereka agar tetap sehat. “Sehingga tidak hanya pengetahuan tapi juga keterampilan,” tambahnya.
Dalam proses penyampaian pengetahuan, Nida dan kawan-kawan pun menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Mereka melakukan pendekatan emosional dengan menyampaikan materi secara menyenangkan dengan media gambar dan stiker. Sehingga memudahkan anak-anak disabilitas memahami terkait dampak yang akan terjadi jika mereka tidak menjaga alat reproduksi dengan baik.
“Kami ajarin bahwa sehabis buang air kecil dan buang air besar, vaginanya harus dilap terlebih dahulu. Celana dalam harus diganti dua kali sehari. Jadi mereka paham, oh kalau aku tidak melakukan ini dampaknya akan seperti ini.”
Hasil uji hipotesis, edukasi melalui Papan Poppy ini, hampir tujuh puluh persen pengetahuan pada anak disabilitas terkait HKRS meningkat. Ini menunjukkan bahwa metode Papan Poppy yang digunakan Nida dan kawan-kawan sangat efektif dan berpengaruh.
Apa yang dilakukan Nida dan kawan-kawan, jadi bukti bahwa isu HKRS dapat diakses dengan baik terutama bagi anak penyandang disabilitas. Terpenting adalah bagaimana metode yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.
Nida dan kawan-kawan berharap ke depannya kesetaraan akses terhadap isu HKRS meningkat. Serta perspektif masyarakat lebih terbuka untuk memberikan edukasi HKRS kepada anak-anak disabilitas. Masyarakat harus memulai untuk memiliki pandangan bahwa seseorang dengan penyandang disabilitas juga mengalami perkembangan seksualitas yang sama dengan manusia lainnya.
“Mencoba terbuka dan memahami terlebih dahulu. Jadi jangan langsung resistensi dulu. Karena hal ini penting bagaimana mewujudkan kesetaraan akses tersebut. Terakhir, mulai untuk mewujudkan kehidupan yang adil gender,” tutupnya.
Dari cerita Nida dkk, kita dapat belajar banyak bahwa HKRS bagi anak penyandang disabilitas menjadi isu yang penting dan kompleks. Anak-anak dengan disabilitas memiliki hak yang sama seperti anak-anak lainnya. Termasuk hak untuk mendapatkan informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang memadai. Namun, sering kali, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hak ini belum sepenuhnya terpenuhi.
Anak-anak penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan yang unik dalam hal kesehatan reproduksi dan seksualitas mereka. Anak-anak penyandang disabilitas mungkin mengalami ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman mereka. Selain itu, stigma sosial terhadap disabilitas dapat menciptakan lingkungan yang tidak mendukung. Bahkan dapat menjadi penghalang bagi anak penyandang disabilitas untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi.
Mengatasi isu HKRS bagi anak penyandang disabilitas membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, lembaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat secara luas. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusi, kita dapat membantu mereka mencapai potensi penuh dan hidup secara mandiri serta bermartabat.